Pesta Pencuri dan Tradisi Korupsi
Monday, 12 June 2017 - 00:00
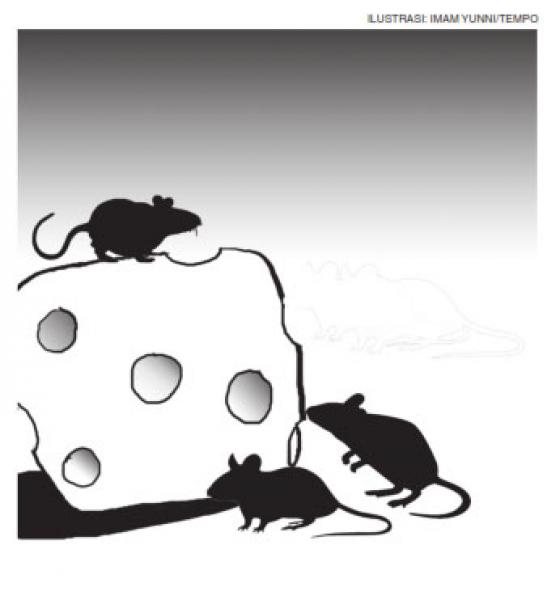
Kasus korupsi eKTP, helikopter AW 101, auditor Badan Pemeriksa Keuangan, dan aliran dana ke “tokoh reformasi” terbongkar. Muncul sebagai berita berturut-turut seperti antrean bebek. Apakah terlalu keliru jika saya teringat judul Pesta Pencuri?
Asrul Sani pada 1976 menggunakan judul itu ketika menerjemahkan lakon Thieves’ Carnival karya Jean Anouilh (1910-1987), yang diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris oleh Eric Bentley. Pesta pencuri! Mengapa tidak? Bukankah itu berlangsung sejak Reformasi 1998 setelah pencuri terbesar disingkirkan dari gelanggang? Ibarat kata, dulu korupsi dilakukan oleh sebuah rezim (sehingga tiada tuntutan ketika masih berkuasa), kini korupsi dilakukan
oleh semua orang dan menyibukkan KPK. Enggak mau rugi!
Benarkah ini masalah moral? Artinya, benarkah para koruptor ini sungguh-sungguh bejat? Dalam analisis tentang korupsi di Indonesia pada awal Orde Baru, yakni pada 1971, terdapat klasifikasi korupsi seperti berikut: (1) manipulasi besar di puncak dan (2) metode suap, yakni ketika turun ke bawah dalam bentuk “uang kilat” alias “uang semir” maupun “uang rokok”. Dengan kata lain, terdapat pembedaan kualitatif antara korupsi tingkat tinggi dan korupsi tingkat rendah—dari tingkat nasional sampai ke desa.
Sepintas lalu, yang pertama lebih urgen untuk “langsung ditangkap” dan menimbulkan gelombang berita sensasional karena pelakunya tidak terduga. Klasifikasi pertama ini memang langsung merugikan dan seperti lebih tergolong kategori “mencuri”—di sinilah istilah “moral bejat” itu biasa di timpakan. Namun perhatikan sejumlah penjabaran klasifikasi kedua: (a) pengalihan dana yang berada di bawah pengawasan; (b) menggunakan wewenang resmi untuk memerintahkan pembayaran uang tidak resmi pihak swasta, yang berusaha mendapat hak istimewa atau bantuan pemerintah; (c) pembayaran pribadi pengganti pajak atau demi pemberian izin—yang kedua ini pertaruhannya legitimasi pemerintah, di samping kerugian negara tetap besar.
Para pemimpin antikorupsi, pada 1970-an itu, disebut lebih tersita perhatiannya kepada yang pertama, padahal disebutkan pula bahwa orang jauh lebih sedikit terlibat dalam pencurian langsung dengan terbuka dibandingkan dengan penyuapan. Mengapa begitu? Kemudahan administratif dan “keterjangkauan penangkapan” disebut mempengaruhi pilihan itu. Kondisi semacam itu mengundang kritik: pilihan ini merupakan kasus prioritas yang salah tempat (Smith, 1971: 21-40).
Jika pendekatan ini masih berlangsung, bahwa korupsi para bos tentu lebih besar daripada korupsi sistemik yang melibatkan berjuta-juta pegawai rendah, analisis mutakhir dari sudut pandang sejarah menunjukkan bahwa krisis finansial pada 1786 membuka pintu bagi Revolusi Prancis dan kehancuran sistem kerajaan. Ini menjadikan isu korupsi bukan hal yang ringan, tidak bisa dimaafkan, dan tidak bisa dibiarkan karena langsung menyangkut keselamatan negara (Carey dalam Carey & Haryadi, 2016).
Dalam konteks Indonesia, variabel sejarah menunjukkan sejumlah faktor yang membuat korupsi terjadi: (1) kebijakan Vereenigde OostIndische Compagnie (VOC) alias Kumpeni memberi gaji terlalu rendah kepada pegawai setempat, mempermudah metode suap dalam pengawasan dari negara asal yang terlalu lemah; (2) kebangkrutan Kumpeni yang membuatnya diganti Gubernur Jenderal Belanda pada pergantian abad ke19, membuat praktik terlarang meluas tanpa bisa dihindari—bandingkan dengan “pesta pencuri” sejak Reformasi 1998; (3) uang jasa dan pembayaran tradisional pejabat pribumi aristokratis yang diganti gaji dari Belanda membuat pejabat pribumi tidak punya pilihan selain menggunakan cara-cara tidak sah untuk mempertahankan gaya hidupnya (Day, 1966).
Adapun tesis Soemarsaid Moertono (1922-1987) perihal tata negara Kerajaan Mataram abad ke-16 hingga ke-19 telah menunjuk fakta yang menjadi latar belakang dengan melampirkan piagam jabatan bekel. Terungkap bahwa bekel harus membayar uang pungutan kepada raja, kewajiban khusus kepada lurah, sumbangan pesta putri raja, dan sebagainya (Moertono, 1985: 167), yang tidak dengan jelas menegaskan keterpisahan pribadi dan pemerintah. Aturan ini menjadi “tradisi”, yang mungkinkah membuat pemahaman “korupsi”, bahkan sampai abad ke-21 hari ini belum juga dikenali sebagai kebersalahan? Setelah dua abad, lebih dari keterlaluan jika ketidaktahuan atas peralihan wacana itu—dari kerajaan, jajahan, ke republik sengaja dan tak sengaja dilestarikan.
Apakah dengan begitu pula lantas korupsi sistemik membebaskan para pencuri dari tanggung jawab moralnya? Dalam lakon Pesta Pencuri terdapat ujaran berikut: “….waktu Tuhan menciptakan pencuri, Ia harus mempereteli beberapa miliknya, lalu Ia ambil dari mereka rasa kehormatan manusia yang jujur.”
SENO GUMIRA AJIDARMA PANAJOURNAL.COM
------------------
Versi cetak artikel ini terbit di Koran Tempo edisi 12 Juni 2017, di halaman 11 dengan judul "Pesta Pencuri dan Tradisi Korupsi".










