Pandora Papers: Kegagapan Negara Atas Kejahatan Lintas Negara
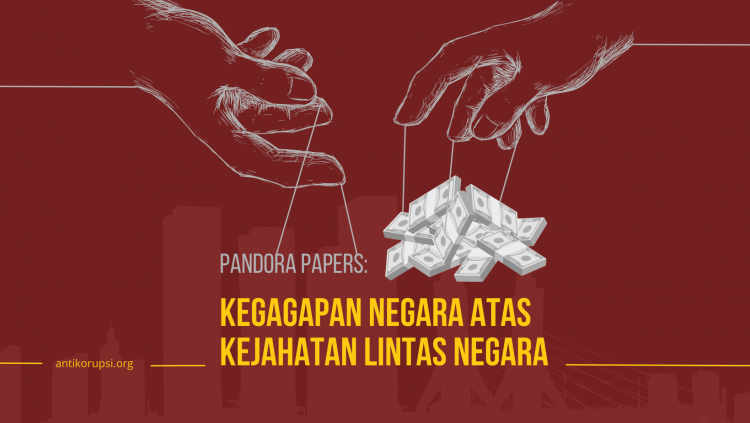
Beberapa tahun lalu, dunia internasional digemparkan dengan skandal kejahatan finansial Panama Papers dan Paradise Papers yang diungkap oleh kolaborasi jurnalis yang tergabung dalam International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Kini ICIJ kembali mempublikasikan Pandora Papers, di mana ratusan nama politisi dan pejabat publik dari berbagai negara termasuk dari Indonesia karena diduga melakukan penggelapan atau menghindari kewajiban pajak.
Seperti diketahui dalam kasus Panama Papers yang dipublikasikan pada 3 April 2016, terdapat sejumlah nama pejabat publik Indonesia seperti Airlangga Hartarto –ketika itu menjabat sebagai Anggota DPR RI– dan Luhut Binsar Panjaitan –ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan– serta taipan seperti Keluarga Ciputra, Garibaldi Thohir, termasuk terpidana korupsi Joko Tjandra
Munculnya kasus Pandora Papers yang kini memuat nama pengusaha Indonesia membuat publik mempertanyakan keseriusan pemerintah mengatasi kasus dugaan penghindaran atau penggelapan pajak. Pertanyaan itu muncul karena otoritas keuangan Indonesia seperti Kementerian Keuangan dan PPATK berjanji akan menindaklanjuti temuan sebelumnya baik lewat pengecekan SPT maupun lewat penelusuran transaksi lebih lanjut oleh PPATK. Namun, hingga data leaks Pandora Papers terungkap, belum ada kejelasan terkait tindak lanjut konkrit dari pemerintah.
Kepemilikan perusahaan cangkang sebagai special purposed vehicle (SPV) maupun kepemilikan akun pada wilayah keuangan lepas pantai (offshore territory), memang bukan merupakan tindak pidana. Namun harus diingat jika skema transaksi keuangan lintas negara yang kompleks –seperti transfer pricing– yang “melibatkan” wilayah keuangan lepas pantai maupun negara suaka pajak (tax havens), kerap digunakan untuk menutupi kejahatan keuangan seperti pengelabuan pajak (tax evasion), korupsi dan pencucian uang.

Meski Indonesia sudah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali penerima manfaat untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, namun Perpres ini dianggap masih mengadung kelemahan.
Kelemahan pertama adalah tidak adanya pengecekan profil terkait nama yang didaftarkan sebagai pemilik manfaat utama dari sebuah korporasi (beneficial owner-BO). Sehingga masih ada kemungkinan nama yang didaftarkan sebagai BO bukanlah pemilik manfaat utama yang sebenarnya, tidak ada hukuman yang jelas atas pengelabuan tersebut. Ketiadaan sanksi dalam Perpres BO juga hampir serupa dengan aturan dalam penyampaian LHKPN yang tidak mengatur sanksi jika ada keterlambatan atau penyampaian informasi harta secara tidak benar.
Kedua, Perpres tersebut tidak dapat menjangkau perusahaan yang didirikan di luar negeri oleh warga negara Indonesia. Berkaca pada kompleksitas penanganan perkara yang melibatkan skema transaksi keuangan lintas negara, seperti Asian Agri Group dan kasus korupsi Bank Century dengan terdakwa Rafat Ali Rizvi dan Hesjam Al Warraq. Hingga kini, pemulihan kerugian negara dari kedua perkara tersebut belum optimal.
Berdasar penjelasan di atas, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas pada tataran regulasi dan penegakannya. Pertama, Perpres 13/ 2018 harus “naik kelas” hingga tataran undang-undang, sehingga ada sanksi pidana yang jelas untuk perbuatan pengelabuan informasi sekaligus untuk memperluas jangkauan pelaporan hingga kepemilikan perusahaan WNI di luar negeri.
Kedua, Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan mengakomodasi norma illicit enrichment ke dalam UU Tipikor. Hal tersebut sejalan dengan Konvensi PBB Anti-Korupsi, yang telah diratifikasi pula oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.










