Mendesain Pilpres Antikorupsi
Saturday, 01 July 2017 - 00:00
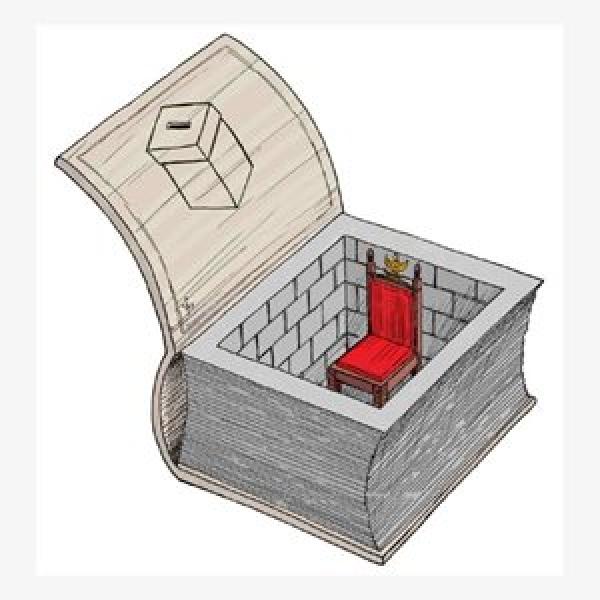
Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, menjelang ritual lima tahunan pemilihan presiden, proses legislasi kita dipenuhi perdebatan syarat ambang batas dukungan partai politik dalam mencalonkan presiden (presidential threshold).
Syarat calon presiden (capres) menjadi kunci perdebatan dan menggiring pembahasan sistem pemilu yang lain menuju jalan buntu. Masih lekat dalam ingatan kita ketika dalam pembahasan RUU Pemilihan Presiden pada awal Reformasi, setiap parpol melakukan tukar-guling aturan demi meloloskan figur capres yang didukungnya.
PDI Perjuangan mendapatkan syarat pendidikan minimal SMA untuk Megawati Soekarnoputri. Golkar menggugurkan syarat bebas dari masalah hukum bagi Akbar Tandjung. PKB mendapatkan syarat "mampu" bagi Abdurrahman Wahid. PAN mendapatkan aturan peralihan syarat dukungan partai bagi Amien Rais.
Proses legislasi pasti tidak akan steril dari kepentingan politik partai. Berharap partai tidak memasukkan kepentingan strategi pemenangan ke dalam pembahasan UU kepemiluan adalah bagaikan pungguk merindukan bulan. Itu adalah hal yang nyaris mustahil. Pilihan aturan hukum sekarang pasti berkait erat dengan strategi pemenangan Pilpres 2019. Pertarungan telah dimulai sejak perumusan syarat menjadi capres. Yang perlu kita kawal adalah bagaimana proses legislasi yang sarat kepentingan itu tetap sejalan dengan agenda bangsa, utamanya antikorupsi. Bagaimana perumusan syarat capres akan menghadirkan sistem pilpres yang antikorupsi?
Sistem pilpres antikorupsi
Presiden adalah figur sentral dalam sistem presidensial. Demikian pula dalam agenda pemberantasan korupsi. Presiden adalah panglima perang menumpas koruptor. Tanpa presiden yang berkomitmen terang-benderang, maka perjuangan melawan korupsi akan terus terjebak dalam kelam kekalahan. Karena itu, harus didesain sistem pilpres antikorupsi, yaitu sistem yang membuka ruang bagi figur antikorupsi untuk mencalonkan diri dan akhirnya terpilih menjadi presiden, serta kemudian mendapatkan dukungan politik yang cukup untuk menegakkan agenda pemberantasan korupsi.
Karena sistem pencalonan presiden kita dikuasai oleh partai politik dan tidak membuka pintu bagi calon presiden independen, komitmen antikorupsi partai menjadi kunci bagi lahirnya presiden yang antikorupsi. Celakanya, di situlah letak persoalan utama kita, konfigurasi politik kita masih terjebak dalam maraknya praktik korupsi. Jika kita mengacu pada kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi, tak ada satu pun partai yang bersih dari jeratan perkara korupsi.
Inilah salah satu dilema sistem presidensial kita, yaitu bagaimana upaya penyederhanaan partai tetap sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Telah banyak penelitian yang menyimpulkan sistem presidensial tidak sejalan dengan sistem multipartai. Salah satu yang sering dirujuk adalah artikel Scott Mainwairing (1993), dalam jurnal Comparative Political Studies berjudul "Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Difficult Combination". Namun, persoalan korupsi yang menjerat parpol kita, apalagi makin kuat partainya, maka godaan korupsinya juga cenderung semakin besar, menyebabkan kita harus tetap membuka ruang bagi partai baru yang membawa harapan antikorupsi. Maka, saya setuju ambang batas parlemen (parliamentary threshold) secara bertahap dinaikkan. Dalam hal ini, kita sudah pada jalur yang benar.
Presiden minoritas
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden harus dilaksanakan serentak, perdebatan soal ambang batas calon presiden tidak kunjung usai. Saya sendiri berpandangan, memang tidak ada kejelasan aturan konstitusi yang melarang presidential threshold. Putusan MK hanya menegaskan pelaksanaan pemilu serentak, tetapi tidak membahas soal konstitusionalitas ambang batas presiden. Maka, soal presidential threshold adalah kebijakan hukum yang terbuka dan bergantung pada pilihan politik legislasi.
Ada pendapat bahwa pemilu serentak (concurrent election) akan menghadirkan presiden yang lebih efektif ketimbang pemilu tidak serentak (consecutive election). Dalam pemilu serentak, jumlah partai akan cenderung turun. Karena, untuk mendongkrak suaranya, partai kecil memilih berkoalisi dan mendukung figur capres yang paling mungkin menang. Yang pasti, dalam pemilu serentak, kesempatan untuk membangun kontrol parlemen kepada presiden akan semakin sulit. Dalam pemilu tidak serentak, pemilih bisa melakukan pemilihan presiden yang berbeda dengan partai pendukungnya (split ticket). Hal demikian tidak mungkin dilakukan dalam pemilu serentak.
Maka dalam pemilu serentak, kecenderungan hadirnya presiden minoritas (minority president), yaitu presiden yang tidak mendapatkan dukungan politik mayoritas di parlemen, kemungkinan akan lebih kecil. Menurut hitungan Jose Antonio Cheibub (2002), dalam artikelnya berjudul "Minority Governments, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential Democracies" dalam jurnal Comparative Political Studies, pemilu serentak hanya menghadirkan presiden minoritas 31,3 persen, berbanding dengan 56,4 persen pada pemilu yang diselenggarakan pada waktu yang berbeda.
Ambang batas presiden
Dengan ambang batas parlemen yang sudah naik gradual dan sistem pemilu serentak yang lebih membantu hadirnya sistem presidensial yang tidak minoritas, ruang agar konfigurasi politik tidak dikuasai oligarki partai yang korup adalah memperbesar ajang kompetisi pemilihan presiden. Bagaimanapun sistem yang kompetitif akan membuka ruang demokrasi yang lebih lebar ketimbang sistem yang monopolistik.
Ruang kompetisi itu jangan menghilangkan sama sekali syarat ambang batas presiden. Bukan semata tanpa presidential threshold insentif menuju sistem penyederhanaan partai akan mengecil, tetapi secara teori dan praktik, tidaklah mungkin ada presiden yang efektif tanpa dukungan politik sama sekali di parlemen.
Bahkan, seorang presiden independen sekalipun tak mungkin meniadakan sama sekali syarat dukungan politik parlemen bagi jalannya pemerintahan yang dipimpinnya. Harus dicatat, presiden yang menang pilpres dan dapat dukungan pemilih (electoral support) yang mayoritas, tak akan bisa efektif melakukan banyak hal tanpa dukungan politik parlemen (political support).
Namun, ambang batas presiden 20 atau 25 persen seperti yang saat ini berlaku juga tidak layak dipertahankan karena tidak membuka ruang kompetisi yang cukup, dan cenderung melanggengkan oligarki parpol yang koruptif. Maka, saya sepakat ambang batas presiden diturunkan. Berapa besaran angkanya adalah ruang pilihan politik. Pilihan paling kecilnya adalah sama dengan ambang batas parlemen. Sehingga setiap partai yang mempunyai kursi di DPR hasil Pemilu 2014 mempunyai hak untuk mengajukan capres.
Lalu bagaimana dengan partai-partai baru peserta Pemilu 2019? Mereka belum berhak mengajukan capres. Bagaimanapun, semua partai harus membuktikan dirinya layak dan mendapatkan dukungan rakyat pemilih, dengan mempunyai anggota di parlemen, sebelum berhak mengajukan capres pada pemilu berikutnya.
Tetap harus diakui, penurunan ambang batas presiden bukan jaminan pasti akan hadirnya presiden yang antikorupsi. Yang dapat dipastikan adalah terbukanya ruang kompetisi yang lebih lebar, melalui hadirnya capres alternatif. Sementara potensi korupsi pencalonan tetap tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Tidak ada satu sistem pun yang imun dari praktik korupsi. Hanya modusnya saja yang berubah-ubah.
Dalam sistem dengan ambang batas presiden yang tinggi, praktik korupsi dilakukan dengan modus parpol menjual tiket perahu kepada kandidat atau partai. Inilah modus pembelian tiket partai untuk menjadi kandidat (candidacy buying). Sebaliknya, dalam sistem ambang batas yang lebih rendah, yang merangsang hadirnya capres-capres alternatif, parpol atau sang calon alternatif menjual peluangnya sebagai kompetitor yang dapat mengeruk lumbung suara pemilih yang sama. Inilah modus penjualan tiket tokoh partai untuk tak jadi kandidat (no-candidacy buying).
Saat ini, dalam pembahasan RUU Pilpres, posisi pemerintah adalah mempertahankan presidential threshold pada angka 20 atau 25 persen. Mungkin, Presiden Jokowi berhitung syarat itu memberi peluang lebih besar baginya untuk terpilih kembali. Mari, sama-sama kita tunggu ke manakah ujung pembahasan syarat pilpres ini akan berakhir. Apakah menuju kepentingan jangka panjang untuk menciptakan sistem pilpres yang lebih antikorupsi ataukah justru melanggengkan koalisi oligarki partai yang cenderung koruptif.
DENNY INDRAYANA, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Profesor Tamu di Melbourne Law School dan Faculty of Arts University of Melbourne, Australia
-------------------
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Mendesain Pilpres Antikorupsi".










